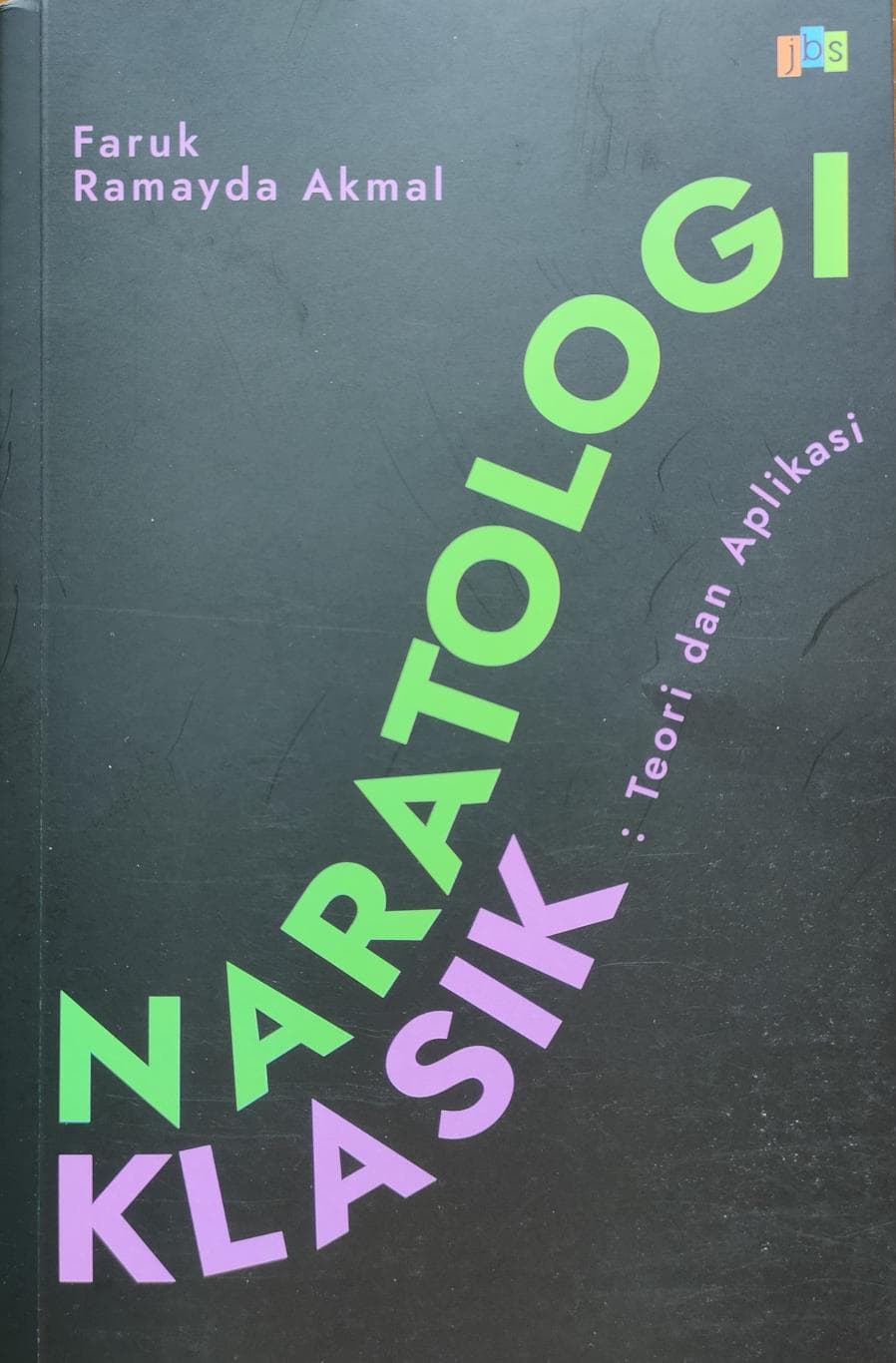Buku ini menjadi bacaan yang tepat bagi ekosistem studi sastra. Bukan sekadar mengungkap konsepsi penting, melainkan sekaligus memadukannya dengan praktik analisis terhadap objek material berupa karya sastra.
Cerita bukan hanya ”apa” (isi, substansi) yang terjadi, melainkan ”bagaimana” (strategi, mekanisme) ia diceritakan. Di sanalah emosi, makna, dan ideologi dibentuk.
Di tengah praktik kritik sastra yang sering berhenti pada ”apa isi cerita”, buku ini mengajak pembaca beralih ke pertanyaan yang lebih menentukan: ”bagaimana cerita bekerja” atau ”persoalan teknik penceritaan”.
Konoteks itu menempatkan pembedaan klasik teks-cerita-fabula sebagai fondasi. Pembaca diingatkan bahwa teknik penceritaan –urutan, tempo, sudut pandang, suara– bukan sekadar hiasan struktural, melainkan lensa yang mengarahkan emosi, makna, bahkan bias ideologis.
Buku yang ditulis sebagai hasil riset dalam skema Guru Besar FIB UGM Prof Faruk, yang menggandeng juniornya, Ayda (Ramayda Akmal), ini mengulik naratologi dengan membatasi pada rentang waktu klasik.
Di sisi lain, rentang masa pascaklasik barangkali dapat disusun dalam seri karya akademik berikutnya. Termasuk perhatian terhadap perkembangan mediumnya: media bahasa lisan, media visual, multimedia, hingga penuturan cerita intermedial.
Membumikan Konsepsi Genette dan Bal
Buku yang sempat tertunda terbit ini –harusnya, sesuai skema, telah terbit 2023– berikhtiar membumikan konsepsi naratologi Gerard Genette dan Mieke Bal. Bukan sekadar mengungkap konsepsi penting, melainkan sekaligus memadukannya dengan praktik analisis terhadap objek material berupa karya sastra.
Naratologi dari Genette dan Bal disusun ulang menjadi perangkat praktis yang rapi, terukur, dan siap pakai di ruang kelas, riset akademik, maupun kerja kreatif penulisan.
Pada ranah Genette, lima kunci bekerja sebagai mesin analisis yang sederhana tetapi tajam: urutan, durasi, frekuensi, modus, dan suara (hal 66–88). Urutan menawarkan strategi memundurkan (analepsis) atau memajukan (prolepsis) peristiwa demi efek kejutan, empati, atau suspens.
Durasi (tempo) memunculkan perbandingan waktu cerita dan waktu tuturan –adegan, ringkasan, elipsis, jeda– untuk membaca intensi pengarang ketika sengaja mengulur atau memadatkan makna.
Di sisi lain, frekuensi menitikberatkan pada relasi ”berapa kali terjadi” dan ”berapa kali dituturkan” (singulatif, repetitif, iteratif); sedangkan modus berurusan dengan dimensi seberapa dekat jarak penceritaan (ujaran langsung, tidak langsung, free indirect style) dan siapa yang mengetahui (fokalisasi, internal, eksternal).
Sementara itu, fokus suara berkelindan dengan siapa yang bertutur (narator heterodiegetik/bukan tokoh, atau homodiegetik/tokoh) dan dari level mana (ekstradiegetik, intradiegetik, hingga metadiegetik/cerita di dalam cerita).
Pada ranah Bal, menambah ketelitian melalui tiga tingkat: teks, cerita, dan fabula (hal 133–172). Sekaligus pembedaan yang sering membebaskan pembaca dari kekacauan sudut pandang: narator (si pembicara), bukan fokalisator (si pelihat). Di sini, ”mata” yang melihat tidak selalu sama dengan ”suara” yang berbicara.
Bal juga menekankan peristiwa sebagai perubahan keadaan, membedakan aktor (agen tindakan) dari tokoh/karakter (aktor yang telah mendapat atribut), dan menggarisbawahi ruang sebagai pengarah tafsir (bukan sekadar latar pasif).
Kekuatan buku ini di antaranya tampak pada menyatunya teori dan aplikasi. Penulis menawarkan prosedur langkah demi langkah. Naratologi Genette diterapkan untuk menganalisis novel Gentayangan karya Intan Paramaditha, 2017 (hal 89–131), sedangkan naratologi Bal diaplikasikan pada cerpen ”Robohnya Surau Kami” karya A.A. Navis, 1961 (hal 173–245; 247–326).
Dari penerapan lima kunci Genette, penulis bukan hanya mampu membedah struktur, karakteristik genre, hingga ideologi pengarang, melainkan juga faktor sosiologis dan psikologis novel Gentayangan.
Demikian juga aplikasi naratologi Bal. Penulis dengan menghayati tiga strategi –teks, cerita, fabula– sampai pada pemaknaan bahwa kisah ”Robohnya Surau Kami” menjadi artikulasi historis dan literer atas modernisme Islam.
Praktik analisis kedua karya itu menjadikan teori terasa membumi: akademisi dapat mengubahnya sebagai lembar kerja, peneliti dapat menurunkannya ke desain analisis, dan penulis bisa mengecek ”mengapa” satu teknik penceritaan lebih menggugah daripada yang lain.
Menajamkan ”Mata” Cerita
Buku ini konsisten mengingatkan bahwa setiap pilihan teknis –menggeser urutan, memanjangkan adegan, mengunci fokalisasi ke batin tokoh tertentu– punya konsekuensi ideologis. Pembaca dilatih peka terhadap objek fokalisasi (apa yang diperlihatkan/disembunyikan), bias narator, dan otoritas level penceritaan.
Dengan begitu, naratologi tak lagi terasa sebagai hitungan mekanis, tetapi kompas etis untuk membaca kuasa wacana dalam cerita. Kisah tak cukup dipahami tentang ”apa”, tetapi perlu dihayati tentang ”bagaimana”. Strategi ini mampu menajamkan ”mata” cerita sehingga dapat dirasakan roh ideologis yang dibentuknya.
Baca Juga
Transformasi Profetik Teater Eska
Keunggulan buku ini terletak pada daya dalam menajamkan ”mata” cerita. Penyajiannya sistematis. Penyederhanaan istilah tanpa kehilangan akurasi. Menyatunya teori-praktik yang cukup memandu. Penajaman isu narator versus fokalisator (Bal) dan waktu-suara (Genette) juga relatif fungsional.
Bagi pembaca pemula, tetap memerlukan disiplin mengerjakan peta waktu dan tabel fokalisasi agar hasil analisis lebih eksplisit. Meskipun demikian, rambu-rambu buku telah menyediakan rel yang memudahkan proses itu.
Buku ini menjadi bacaan yang tepat bagi ekosistem studi sastra. Ia memberi alat yang ketat tetapi lentur, teoretis tetapi aplikatif. Untuk akademisi (mahasiswa-dosen) yang butuh perangkat kuliah, peneliti yang menuntut ketepatan kategori, dan penulis-editor yang ingin menguasai ”mesin” efek naratif, buku ini bukan sekadar referensi, melainkan panduan kerja.
Pada akhirnya, memahami cerita bukan hanya perkara mengetahui ”apa yang diceritakan”, melainkan menghayati siapa yang bicara, siapa yang melihat, dari mana, kapan, dan dengan tempo bagaimana? Di situlah makna –dan ideologi– dibangun, dipertarungkan, dan dipertanggungjawabkan. (*)
Judul : Naratologi Klasik: Teori dan Aplikasi
Penulis : Faruk dan Ramayda Akmal
Penerbit : JBS
Cetakan : Pertama, Agustus 2025
Tebal : xii + 350 halaman
Format : 15 × 23 cm
ISBN : 978-623-8755-20-2
Heru S.P. Saputra
Koordinator Kelompok Riset Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal Fakultas Ilmu Budaya serta Koordinator Pusat Riset Metakultura Universitas Jember