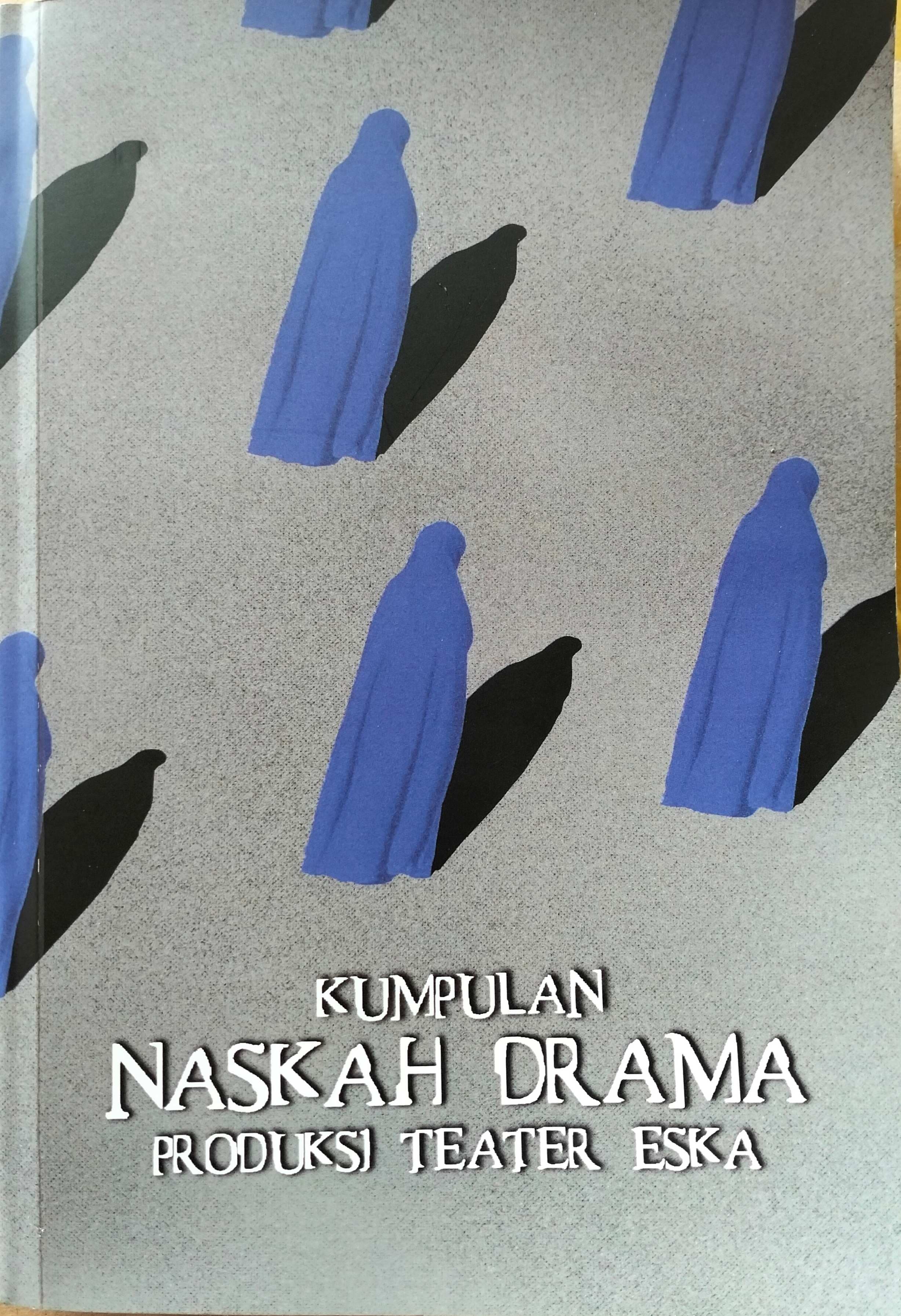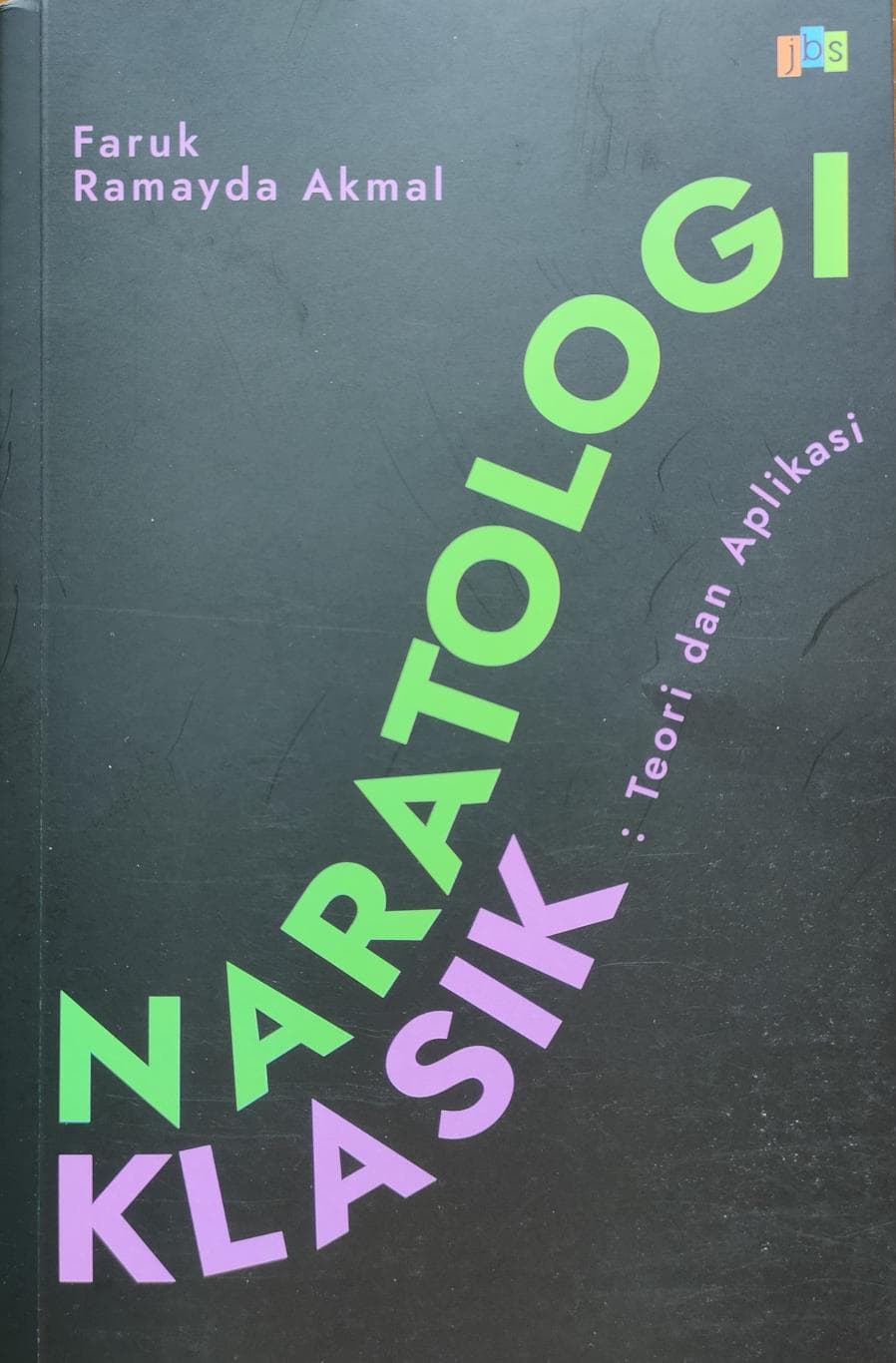Teater Eska merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mewarnai jagat teater kampus lebih dari empat dekade. Ulang tahunnya ke-45, 18 Oktober, dirayakan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya menerbitkan buku kumpulan naskah drama yang pernah mereka pentaskan. Berisi 14 naskah, ditulis lintas generasi: Kaji Habeb, Hamdy Salad, Otto Sukatno Cr, Edeng Syamsul Maarif, Shohifur Ridho, Ghoz Te, Zuhdi Sang, HR Nawawi, dan Habiburracman.
Buku ini mendokumentasikan perjalanan Teater Eska, bukan saja terkait pentas mereka, namun juga membuka tirai estetik dan menyingkap visi-misi berkeseniannya. Hamdy Salad, ideolog kelompok ini, menyatakan bahwa Teater Eska mengalami metamorfosis dari seni dakwah ke seni hikmah, untuk akhirnya sampai pada wacana teater profetik.
Pilihan bentuk ekspresinya nonrealis dan bersifat religius. Ini sesuai watak seni Islam yang cenderung nonrealis sebagaimana seni arabesque, figuratif, deformatif, transfiguratif, almiskat, i’tibar, alkhayali, sufistik, tauhid, dan seterusnya (Prolog, hal 12-22).
Selain ideologis, menurut saya ada alasan taktis. Mengangkat nilai dan kisah kenabian (waratsatul anbiya), pasti kesulitan secara teknis propertis. Bentuk nonrealis dipilih karena mengandalkan imajinasi untuk menghubungkan penonton dengan kisah kenabian yang dirujuk.
Persoalannya, naskah mereka tak sepenuhnya tertib ”pakem”, baik bentuk maupun isi. Dalam arti, naskah-naskah tersebut juga mengalami metamorfosisnya sendiri, dari waratsatul anbiya menjadi kisah-kisah sosial politik aktual. Hamdy menyebutnya dari ekspresi ke alegori.
Empat Dekade
Editor Bernando J. Sujibto membagi naskah menjadi empat dekade berdasarkan waktu penulisan/pementasan. Pada Dekade Pertama, tahun 80-an, ada naskah Wahsyi, Pembunuh Singa Padang Pasir karya Hamdy Salad. Perspektifnya masih normatif, plot bertumpu pada cerita mainstream terbunuhnya Hamzah, pamanda Rasulullah oleh Wahsyi. Di sini, orientasi Eska diletakkan: kisah kenabian sebagai sumber ilham nan mencerahkan atawa membebaskan.
Namun, di Dekade Kedua (90-an), orientasi itu mendapat tantangan. Lima naskah mulai bertransformasi. Saru Siku karya Otto Sukatno bertokoh manusia keseharian: Mas Ndalem, Mas Klentung, dan Ibu. Mereka menghadapi situasi kisruh. Protes sosial ala Teater Koma dan nuansa Arifin C. Noer dalam absurditas kehidupan wong cilik cukup terasa. Minat Eska atas masalah sosial politik kentara.
Jika Saru Siku melihat kekuasaan dari luar, dari wong cilik, naskah Dan Anak-anak pun Bertaring karya Kaji mengulik kekuasaan dari dalam. Pemainnya langsung aktor kekuasaan itu sendiri, Tuan Go, yang menolak regenerasi kekuasaan. Bahasanya masih dogmatis, kecuali di beberapa bagian agak simbolis.
Pendekatan kekuasaan dari dalam, alih-alih membuat Eska terperangkap isu menara gading. Tapi situasi ini malah dikukuhkan Hamdy dalam Sihir Mata Hitam. Isi dialog para tokohnya cenderung ”tinggi” dengan bahasa metaforis-retoris ala istana. Meski dari sinilah Hamdy mencoba menghela teks ke ranah teater profetik melalui sejumlah dialog berhikmah.
Bahkan konsepsi teater profetik itu tersua dalam dialog Paman: Bukankah nabi pada hakikatnya juga seorang manusia? Dan karena itu kita berhak untuk meniru karakter nabi, dan tentu saja tanpa mengaku sebagai nabi. Sebab nabi palsu telah lahir di mana-mana, di setiap ruang dan waktu (hal 120).
Hamdy meneruskan upaya profetiknya di naskah Berdiri di Tengah Hujan. Ia seperti melanjutkan Sihir Mata Hitam, hanya bahasanya lebih liris. Tokoh utamanya masih Paman, karakternya sama, ucapannya mulai filosofis. Untuk plot, ia pinjam kisah kenabian populer: pelayaran Nabi Yunus sampai ditelan ikan paus. Tapi sayup-sayup menyusup kisah Malin Kundang dari Nenek Renta (Ibu) yang mencari anaknya pulang berlayar. Jika ini dilanjutkan, kemungkinan Eska bisa bergulat pula dengan wacana lokalitas.
Tiba-tiba, naskah Kaki Langit dan Selembar Daun Kering karya Edeng Syamsul Maarif menarik Eska ke gaya realis. Tokoh-tokohnya amat familier: Sastro (Kakek), Kacung (Cucu), Parmi (Ibu). Hanya di sejumlah adegan berpola imajinatif, misalnya saat menggambarkan keindahan surga. Tapi roh profetiknya masih terjaga karena aura ceritanya mengingatkan pada cerpen Kuntowijoyo, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga.
Dekade Ketiga, Kaji Habeb melalui Di Atas Bangku Kosong mempertahankan gaya realis, dengan intensitas pada dialog. Tokohnya juga familier: Tuan Rumah, Anak, Bapak, Anak Muda. Ceritanya tentang regenerasi. Isu sosial-domestik digabung dengan unsur profetik.
Perbatasan Hari (Kaji dan Edeng) kembali melirik kisah kenabian, namun digabung dengan peristiwa sosial aktual. Kehidupan orang-orang pasar menjadi latar perjalanan Raja (Aku) dan Saat, pembantunya. Plot merujuk kisah Musa dan Khidir. Ada pula dialog Masitoh dan Hawa. Tapi melalui orang biasa di pasar, kisah besar seputar kenabian itu dicairkan. Misal, Hawa bilang, ”Kenapa setiap membicarakan Hawa selalu menanyakan Adam?” Kita tahu, tahun 2000-an, isu feminisme sedang berkisar, dan Eska tak bisa berpaling dari kesadaran membocorkan teks. Meski disayangkan, tak ada penulis naskah perempuan di buku ini!
Naskah Tough Out, Yang Mati dan Yang Hidup Kembali karya Hamdy menghidupkan visi Eska yang sempat mengembang-menguncup seperti parasut. Tokoh-tokoh ala istana bertakhta lagi: Tuan Raja, Tabib, Penyihir, Jendral, Narator. Dalam bahasa Arab, judul bisa dibaca Thogut, merujuk penguasa zalim atau tatanan rusak, juga bisa diartikan sulit keluar dalam bahasa Inggris. Ini merujuk suatu zaman ketika ada pemuda bersembunyi di gua khafi.
Jadi naskah ini kaya nuansa Islam klasik, kontras dengan naskah Hamdy berikutnya, Tiga Bayangan. Tiga tokohnya merepresentasikan studi kekinian: Radin (kapitalis), Kasim (marxis), dan Yatim (Islamis). Tapi kedua naskah sama memiliki intensitas dialog, suasana tenang, dan tokoh-tokohnya tidak meradang sebagaimana dalam periode naskah dakwah.
Naskah Mola Kalijaga (Kaji Habeb) kembali ke unsur-unsur kenabian melalui dialog bijak dan penuh falsafah antara Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar (Abdul Jalil). Ia memungut unsur lokalitas, seolah mendeteksi sejak dini wacana ”Islam Nusantara”. Naskah ini menutup Dekade Ketiga dengan semacam upaya ”kembali ke khitah”.
Kontemporer
Dalam Dekade Keempat terdapat tiga naskah yang teknik penulisannya berpola kontemporer. Setidaknya tokoh hanya terdiri atas Orang 1, Orang 2, dan seterusnya. Judul dan subjudulnya bernuansa sastra mutakhir. Patahan-patahan waktu dalam plot mencerminkan situasi kini yang terfragmentaris. Propertinya futuristik: robotik, manusia besi, Efra berjubah merah berambut api, petasan, dan globe.
Akan tetapi dari segi isi, sebenarnya tak jauh beda dengan sebagian besar naskah yang diniatkan profetik. Dalam Labirin dan Retakan Bayang-bayangmu (Shohifur Ridho), misalnya, dialog Bapak-Anak sangat filosofis dan religius, penuh pencarian akan Yang Hakiki. Begitu pula Khuldi, Pertempuran yang tak Pernah Mati (Ghoz dan Zuhdi), diwarnai dialog filosofis-eksistensialis, tapi dengan kosa kata baru yang puitis.
Bahkan dalam Pancering Penjuru (Nawawi dan Habiburracman), tokoh-tokoh mistik berkelebat: Malakut dan suara-suara ketuhanan.
Apakah ini siklus kembalinya Eska ke awal mula, atau representasi dahaganya manusia modern akan oase profetik?
Tentu ada sekian jawaban. Ini analog dengan proses naskah dan ideologi Eska yang memproduksinya. Selalu ada tarik-ulur, upaya keluar jalur, tapi senantiasa ada kerinduan untuk kembali dengan sesuatu yang baru. Mungkin di sinilah hakikat teater profetik itu. (*)
Judul: Kumpulan Naskah Drama Produksi Teater Eska
Penulis: Hamdy Salad dkk
Penerbit: Satu Spasi
Terbit: Oktober 2025
Tebal: 410 halaman
ISBN: 978-634-96293-2-4
Raudal Tanjung Banua
Baca Juga
Monumen Aib
Pembaca naskah drama, tinggal di Bantul