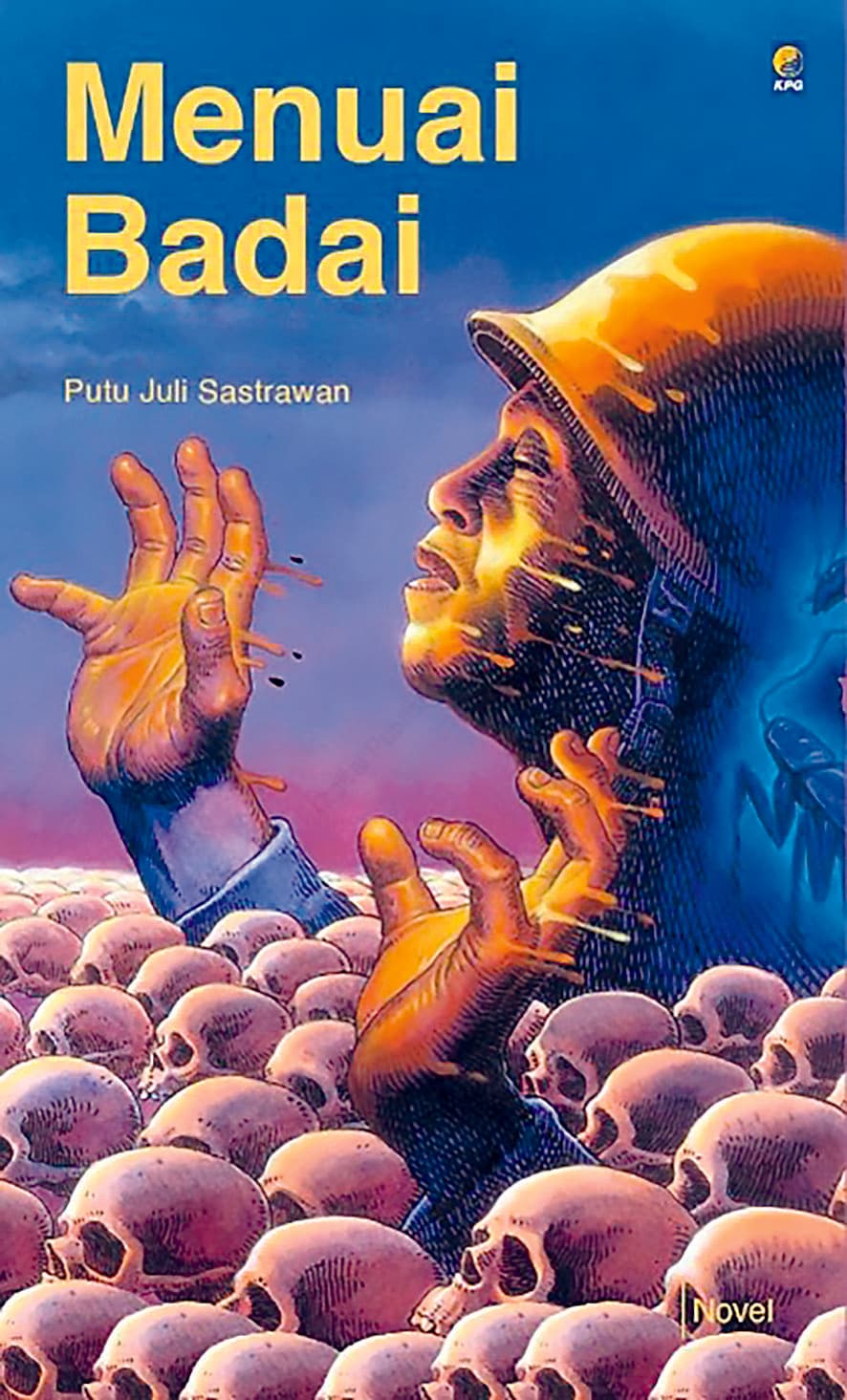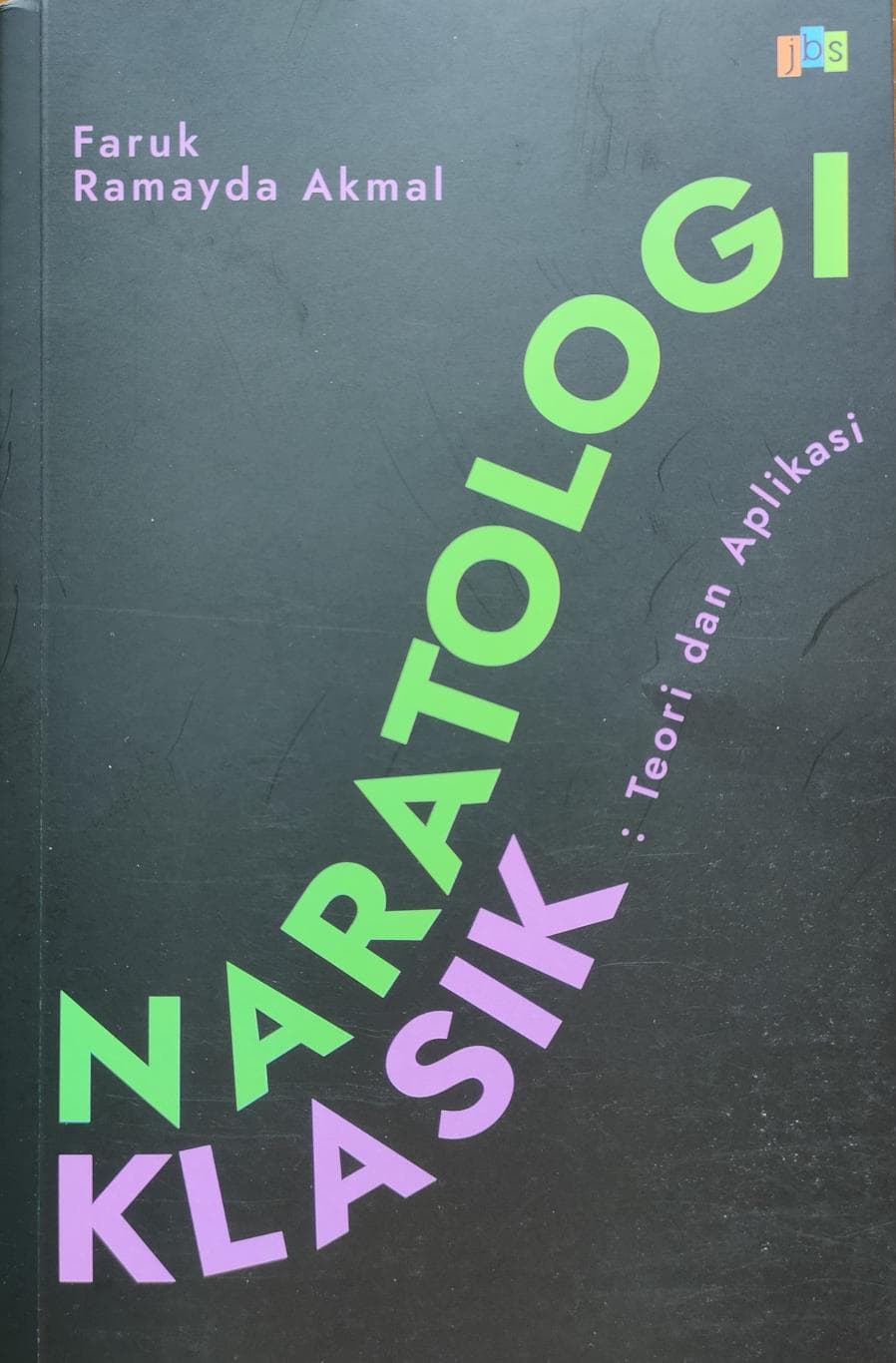Kendati telah enam dekade berlalu, peristiwa 1965 tetap menjadi isu yang tak pernah abstain dalam obrolan di warung kopi, ruang akademik, hingga hiruk-pikuk dunia maya. Ia ibarat api yang menolak mati.
Kita tahu betapa timpangnya informasi tentang peristiwa tragis tersebut. Tak jarang publik kerap memandangnya sebatas kisah penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi militer, lalu dihubungkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Padahal, pasca-penculikan itu, gelombang kekerasan massal justru menyapu negeri ini. Diperkirakan, puluhan ribu hingga jutaan masyarakat sipil terseret dalam penangkapan, pengasingan, penghilangan, hingga pembunuhan secara kolektif, terkhusus sejak wacana ”tumpas PKI hingga ke akar-akarnya” dikumandangkan.
Inilah Menuai Badai. Sebuah novel garapan Putu Juli Sastrawan yang memotret lanskap pembantaian anti-PKI di Bali. Kendatipun, kita tahu, karya sastra yang mengangkat isu tentang 65 jamak ditemui. Sebut saja, misalnya, Ronggeng Dukuh Paruk Ahmad Tohari, Amba Laksmi Pamuntjak, Pulang Leila S. Chudori, dan yang teranyar Dari Dalam Kubur Soe Tjen Marching.
Cerita yang Berbeda
Namun, yang membuat Menuai Badai berbeda adalah ceritanya bukan lahir dari pengalaman para penyintas 65 –seperti tertulis dalam novel-novel di atas, melainkan dari pergolakan batin seorang mantan pelaku pembantaian massal atau yang kerap disebut algojo.
Kandar, si mantan algojo sekaligus tokoh utama dalam novel ini, digambarkan sebagai seseorang yang hidupnya diselimuti kabut tebal. Di dalamnya bergumul penderitaan, penyesalan, trauma, hingga teror yang datang silih berganti. Semua itu menjadi semacam ganjaran atas apa yang dulu ia tabur. Sehingga, sebagaimana diisyaratkan judul novel ini, tibalah saatnya bagi Kandar untuk menuai badai.
”Bahwa sebenar-benarnya hidup yang baik adalah hidup yang mementingkan diri sendiri, menyelamatkan hidup kita sendiri. Apabila selama hidup kita menjumpai dua pilihan: membunuh atau dibunuh, pilihlah untuk membunuh.” (hal 1)
Beginilah Putu Juli Sastrawan membuka ceritanya. Sebuah paragraf yang tampak lebih menyerupai epilog ketimbang prolog. Namun, di situlah justru letak kekuatannya. Ia mampu membuat pembaca berhenti sejenak, mengernyitkan dahi, lalu terdorong terus membaca, hingga menemukan sebuah ironi di baliknya. Sebuah inspirasi yang mustahil lahir tanpa perenungan mendalam.
Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, Juli seolah menghadirkan pergolakan batin yang dialami Kandar ke dalam kepala pembaca. Dengan demikian, pembaca seakan-akan mengalami langsung apa yang dialami oleh Kandar. Di sana, pembaca akan menyaksikan apa yang disebut Juli sebagai ”tubuh sebagai arsip”, yakni ingatan menjadi direktori bagi fragmen-fragmen sejarah yang terpinggirkan.
Keterampilan Juli dalam menyuntikkan pengalaman personal ke dalam sejarah kolektif membuat novel ini terasa intim sekaligus luas cakupannya. Gaya bahasanya yang puitis membuat pembaca lupa dan larut bahwa yang sedang mereka baca adalah kisah tentang darah dan maut. Ia menulis dengan ritme yang lirih, tetapi menghantam pelan-pelan.
Kekuatan Struktural
Melalui Menuai Badai, Juli mengangkat gagasan penting: pelaku pembantaian massal tidak bisa dilihat secara hitam putih. Algojo, dalam novel ini, adalah individu yang terseret oleh kekuatan struktural. Kandar memang pelaku, tapi ia bukan pembunuh yang lahir dari kebencian pribadi, melainkan produk dari situasi politik yang meniadakan pilihan: membunuh atau dibunuh.
Tampaknya, dalam novel ini, Juli memang tidak menawarkan kenyamanan, melainkan mengajak pembaca untuk menafsir, menggali, dan menghadapi guncangan. Ia mengajak pembaca agar mampu merefleksikan ”si pelaku” menjadi manusia yang bisa dipahami –bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk dimengerti.
Salah satu kekuatan novel ini adalah kepiawaian Juli menghadirkan konteks sosial-politik pada masa itu tanpa harus menjadi narasi sejarah yang memberatkan mata alias mengundang kantuk. Misalnya, lewat dialog Koh An dengan seorang mahasiswa di tempat cukur milik Jimakir, menggambarkan situasi Bali saat peristiwa 1965 meletus:
”Suasana tegang menyelimuti Bali saat itu, terutama di wilayah Kabupaten Jembrana. Saya lihat orang-orang dikejar-kejar untuk dibunuh. Memasuki Tabanan, rumah-rumah di pinggir jalan juga dibakar, api terus menyala saat melewati jalanan.” (hal 58)
Sesekali, Juli juga menyisipkan ironi lewat kalimat-kalimat yang sederhana namun menyengat. Ia bercerita sambil menatap realitas, membuat setiap kalimatnya seperti cermin yang memantulkan keburaman sejarah. Misalnya, tentang bagaimana negara lalai merawat ingatannya, Juli menulis dengan getir, ”Negara ini jangankan mengurus arsip yang benda mati, mengurus rakyat yang hidup saja asal-asalan.” (hal 64)
Namun, novel ini bukan tanpa cela. Pilihan Juli menyisipkan kliping surat kabar sezaman mungkin sengaja agar konteks cerita dapat ditangkap. Tetapi, alih-alih memperkaya lapisan narasi, bagian ini justru terasa hanya menempel secara artifisial. Andai saja fragmen-fragmen itu diolah menjadi narasi yang lebih luas, dimensi historis novel ini akan terasa lebih utuh dan menggigit.
Kendati demikian, kehadiran Menuai Badai tetap menjadi angin segar bagi khazanah sastra Indonesia kontemporer. Novel ini menunjukkan bahwa fiksi bisa menjadi cara paling jujur untuk mengingat dan menghidupkan kembali sejarah –bukan melalui klaim kebenaran, melainkan lewat upaya membuka ruang tafsir, dialog, dan narasi-narasi alternatif.
Menuai Badai berbicara jauh dari sekadar prahara 1965. Ia menyinggung watak sebuah bangsa yang kerap enggan mengakui kesalahannya. Dan selama penyangkalan itu terus dipelihara, badai tak akan pernah kunjung reda.
Siapa menabur angin, akan menuai badai. (*)
Judul: Menuai Badai
Penulis: Putu Juli Sastrawan
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun: Cetakan I, Mei 2025
Tebal: vi + 160 halaman
ISBN: 978-623-134-381-9
Wahyu Agil Permana, pegiat sejarah dan promotor @pelitamurba