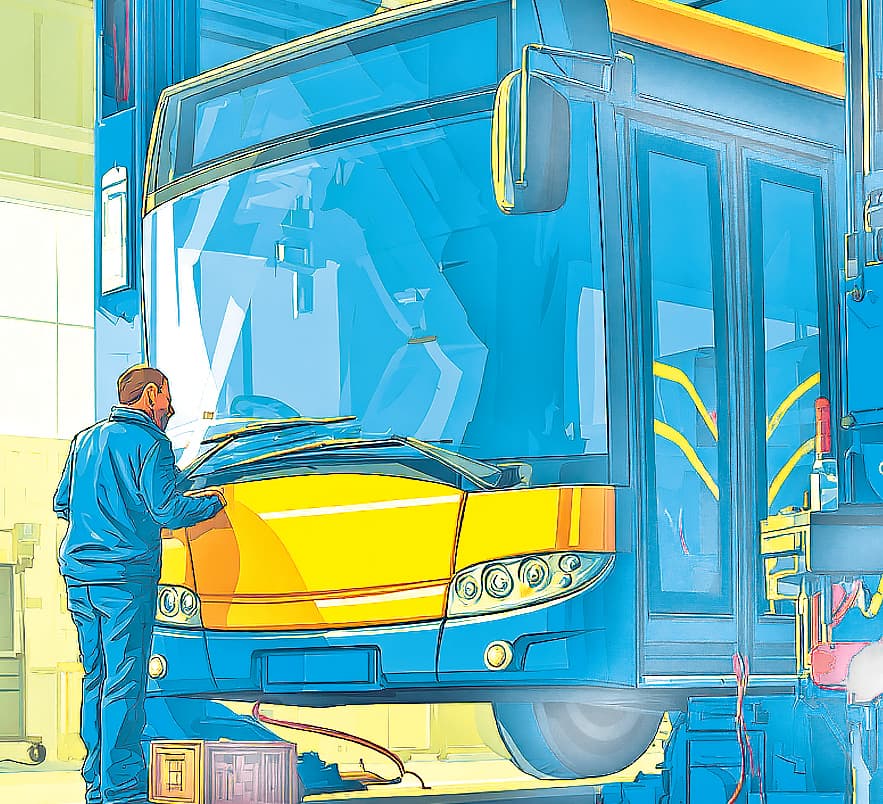Peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas pada 17 November 2025 di SMPN 4 Kota Bekasi menjadi momentum besar dalam upaya transformasi pendidikan nasional. Presiden Prabowo meresmikan langsung distribusismartboard ke sekolah-sekolah. Beliau menyampaikan bahwa sekitar 75 persen satuan pendidikan kini telah menerima perangkat digital tersebut.
Langkah itu jelas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membawa pendidikan Indonesia menuju era baru. Namun, di balik euforia tersebut, ada pertanyaan yang lebih penting: Apa yang ingin kita hadirkan di balik layar digital itu? Apakah digitalisasi itu membangun pendidikan yang berakar pada budaya daerah atau justru mengikisnya?
Tulisan Tangan
Penulis lahir dan dibesarkan di Kabupaten Berau, sebuah wilayah yang kaya dengan budaya dan tradisi literasi lokal. Dulu, saat masih menjadi siswa, penulis begitu akrab dengan tulisan tangan guru yang mengisi papan tulis perlahan-lahan. Tulisan itu bukan sekadar huruf. Tulisan tangan guru di papan tulis itu menjadi jendela ilmu pengetahuan; pelan, teliti, dan penuh makna.
Ketika kemudian mengajar di tingkat SMP sebelum beralih menjadi dosen, penulis menemukan kenyataan unik: setiap siswa memiliki karakter tulisan yang berbeda, mencerminkan cara berpikir mereka. Kini, smartboard masuk menggantikan papan tulis, membawa cara belajar baru ke ruang kelas. Namun, teknologi itu tetap membutuhkan satu hal yang tidak bisa digantikan: konteks budaya di mana siswa hidup dan tumbuh.
Digitalisasi memang membawa banyak manfaat. Namun, sejumlah studi internasional mengingatkan kita bahwa teknologi sering kehilangan makna ketika tidak berpijak pada budaya lokal. Voogt dan Roblin (2022) menyatakan, banyak negara yang gagal memaksimalkan digitalisasi karena konten pembelajaran dibuat terlalu seragam sehingga terputus dari realitas budaya siswa. Gay dan Banks (2021) menegaskan bahwa pembelajaran digital hanya berhasil jika memasukkan identitas lokal –nilai, bahasa, dan tradisi– ke dalam materi yang ditampilkan.
Kearifan Lokal
Jika temuan tersebut kita cerminkan ke Berau, gambaran yang muncul sangat jelas. Kabupaten itu memiliki kekayaan yang luar biasa: legenda Sembilang yang hidup di pesisir, kisah Teluk Semanting, catatan adat yang masih dikelola beberapa kampung, hingga tradisi menulis surat dalam bahasa Berau yang tetap dijaga masyarakat tua.
Baca Juga
Ramp Check
Konteks budaya itu bisa disisipkan pada pelbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, seni budaya, bahkan matematika. Semua ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan hanya ’’muatan lokal’’, melainkan sumber belajar yang mampu memperkaya pengalaman digital siswa.
Namun, kekayaan itu jarang hadir dalam pembelajaran digital. Ketika perangkat datang dari pusat, sering kali materi ajarnya pun ikut berasal dari luar daerah, meninggalkan ruang kelas tanpa jejak identitas lokal.
Padahal, penelitian internasional lain menunjukkan betapa pentingnya konten lokal dalam dunia digital. Zhong (2020) menyebutkan, kesenjangan digital tidak hanya berupa keterbatasan perangkat, tetapi juga ketimpangan antara konten yang relevan dan yang tidak. Takayama dan Lingard (2023) menemukan, pembelajaran digital yang memasukkan budaya lokal meningkatkan rasa memiliki dan motivasi siswa secara signifikan. Sederhananya, anak akan lebih terhubung dengan pelajaran ketika ia melihat dirinya dan dunianya di dalam layar.
Karena itu, penting bagi kita memaknai digitalisasi pendidikan secara lebih luas. Digitalisasi tidak hanya mengganti kapur dengan stylus atau mengganti papan tulis dengan layar sentuh. Digitalisasi adalah bagaimana kita menghadirkan jiwa pendidikan dalam bentuk baru. Dan jiwa itu tidak lain adalah budaya lokal yang membentuk karakter siswa.
Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa konten digital yang ditampilkan di sekolah mencerminkan kehidupan anak-anak sendiri.
Langkah berikutnya adalah memperkuat peran guru. Guru bukan sekadar pengguna teknologi. Mereka adalah kurator konten. Meta-analisis Hennessy (2024) menunjukkan, smartboard memberikan manfaat maksimal hanya apabila guru mampu memasukkan contoh dan konteks lokal ke dalam pembelajaran.
Pelatihan guru harus berfokus pada bagaimana mengolah cerita rakyat, bahasa daerah, atau kearifan lokal menjadi materi digital yang menarik. Di sinilah ruang kolaborasi perlu dibuka –antara sekolah, dinas pendidikan, kampus, komunitas budaya, hingga para penulis lokal. Terakhir, bahasa daerah tidak boleh dilupakan. UNESCO (2023) menemukan bahwa anak-anak memahami pelajaran lebih cepat apabila materi digital menggunakan bahasa atau dialek lokal.
Momen digitalisasi yang dimulai pada 17 November 2025 ini adalah titik penting dalam sejarah pendidikan kita. Namun, sejarah tidak ditentukan oleh kehadiran perangkat, tetapi oleh nilai yang kita tanamkan melalui perangkat itu. Smartboard boleh datang dari pusat, tetapi konten yang mengisi layar harus lahir dari tanah tempat anak-anak belajar dan tumbuh.
Jika digitalisasi ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, ia harus dimaknai dengan prinsip sederhana: teknologi dari pusat, karakter dari daerah. (*)